Senin, 22 Maret 2010 | 08:43 WIB
Oleh: Subhan SD
KOMPAS.com - Sejak kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang cara berpikirnya sering dinilai ”melampaui batas zaman”, apakah Nahdlatul Ulama masih dianggap representasi Islam tradisional?
Bukankah Gus Dur telah membawa arah baru dan pemikiran modern di kalangan kaum nahdliyin, terutama dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan penguatan masyarakat madani.
Persoalannya, corak tradisional itu juga menjadi warna kental dalam manajemen organisasi jam’iyah Islam terbesar di Indonesia itu. Manajemen organisasi secara tradisional dianggap tidak akan bisa mengoptimalkan peran organisasi dalam menghadapi tantangan yang makin kompleks di zaman sekarang ini. Sebab, aspek-aspek manajemen modern, seperti transparansi, akuntabilitas, parameter kinerja yang jelas, atau pola-pola sinergis, tidak terwadahi secara total.
Manajemen tradisional ini jangan-jangan terkait dengan gaya artifisial kaum nahdliyin yang dikenal pula sebagai ”kaum sarungan”. Bahwa corak NU adalah basis di pedesaan, sistem pendidikan di pesantren, pengajaran kitab-kitab kuning), atau cara berpikir dan pemahaman yang toleran dengan tradisi.
Menurut Zamakhsyari Dhofier (Tradisi Pesantren, 1985), sejak pembentukannya, NU menjadi penghadang penyebaran pikiran-pikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa. Pada paruh akhir 1920-an, terjadi status quo ketika kaum modern memusatkan misi di lingkungan perkotaan, sedangkan NU cukup puas dengan basis pendukung di pedesaan.
NU, menurut Kuntowijoyo (Paradigma Islam, 1991), secara kultural sangat terikat dengan konservatisme keanggotaan dan kepemimpinan pedesaannya. Soal dikotomi tradisional (konservatif) dan modernis, meskipun kurang begitu pas, barangkali apa yang dipaparkan Clifford Geertz dalam teks klasiknya, Abangan, Santri, dan Priyayi (1981), bisa memberikan gambaran yang lebih jelas.
Pola manajemen NU memang tak lepas dari refleksi pola-pola yang terkonstruksi di pesantren dengan titik sentral pada kepemimpinan kiai, yang merupakan elemen esensial di pesantren. Dalam konteks itulah, dalam pengelolaan sebuah entitas seperti pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan dan karisma personal seorang kiai. Tak mengherankan, dalam kebijakan umum, bukan dilandasi keputusan secara organisatoris, tetapi keputusan perseorangan.
Pola-pola tradisional itu membuat ”orang dalam” pun gerah, terutama mereka yang semakin merasuk dalam konsep-konsep manajemen modern. Bagi KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, dengan manajemen sekarang ini, kualitas pengelolaan organisasi pun kurang baik, antara lain kurang transparan, kurang akuntabel, kinerja tak terukur, serta kurang mampu menggalang pola kerja sama.
Dengan kondisi obyektif demikian, Gus Solah menegaskan, sekarang ini perbaikan organisasi NU merupakan prioritas utama. Slamet Effendy Yusuf, politisi NU yang lama berkarier di Golkar, menyatakan hal senada. ”Modernisasi organisasi NU mutlak dilakukan,” sebut Slamet dalam makalahnya. Sebagai prasyarat, ujar Gus Solah, NU membutuhkan pemimpin yang sadar organisasi, punya budaya berorganisasi, etika organisasi, dan memiliki kemampuan berorganisasi.
Syuriah vs Tanfidziyah
Salah satu penataan penting yang gencar diperbincangkan menjelang Muktamar Ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-28 Maret adalah menyangkut mekanisme dan kewenangan Syuriah sebagai pimpinan tertinggi pengambil kebijakan dan Tanfidziyah sebagai pelaksana (eksekutif). Selama ini, peran kedua lembaga itu mengalami tumpang tindih. Bukan lagi sekadar persaingan, tetapi peran Tanfidziyah justru terlihat lebih dominan. Sebaliknya, peran Syuriah boleh dikatakan tak menonjol.
Dalam sejarahnya, Syuriah selalu dipimpin oleh para kiai yang memiliki otoritas dan kemampuan di bidang agama, sementara Tanfidziyah diisi oleh tokoh-tokoh yang umumnya memiliki kemampuan nonagama dan organisatoris. Dalam menjalankan peran itu, tentu saja warna lembaga tak lepas dari peran dan gaya kepemimpinan tokoh yang menduduki lembaga-lembaga tersebut.
Apabila kita merefleksi ke masa silam, peran sentral Syuriah pernah ditunjukkan KH Wahab Hasbullah saat menjabat rais aam (1947-1971) selepas wafatnya Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari. Sejatinya, Syuriah tidak melibatkan diri dalam persoalan tertentu, apalagi konflik internal. Syuriah harus mampu menjembatani konflik-konflik yang meletup di internal NU. Inilah yang memunculkan wibawa kepemimpinan di Syuriah menjadi kuat. Dalam menjalankan peran itu, KH Wabah dinilai memainkan peran yang baik.
Akan tetapi, sejarah membawa Syuriah menjadi bagian dalam titik pusaran konflik di dalam NU. Menurut Ali Haidar (Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, 1994), Rais Aam KH Bisri Syansuri (1971-1980), sepeninggal KH Wahab, terlibat dalam konflik saat memecat Subchan ZE, Ketua I PBNU, yang pandangannya selalu bertentangan dengan arus besar di NU. Peristiwa lainnya adalah saat Rais Aam KH Ali Maksum (bersama KH As’ad Syamsul Arifin, KH Machrus Ali, dan lain-lain) ”memaksa” Ketua Umum (Tanfidziyah) KH Idham Chalid (1956-1984) mengundurkan diri karena terlalu mengurusi politik (PPP) di samping faktor kesehatan pada 1982.
Tercatat pula konflik antara pejabat pelaksana rais aam, KH Ali Yafie, dan Ketua Umum (Tanfidziyah) KH Abdurrahman Wahid mengenai sumbangan yang berasal dari dana Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1991. Perbedaan pandangan bahkan membuat Mustasyar Am KH As’ad memilih berpisah (mufaraqah) dari duet kepemimpinan KH Achmad Siddiq-KH Abdurrahman Wahid selepas muktamar di Krapyak, Yogyakarta, pada 1989.
Dengan sejarah konflik internal itu, persaingan lembaga pengambil keputusan (Syuriah), pelaksana (Tanfidziyah), dan penasihat (Mustasyar) bisa saja terulang kembali. Apalagi, masalahnya, ketika ketokohan atau figur, katakanlah seperti Gus Dur, terlebih pada saat yang sama pimpinan Syuriah lebih kalem dan kurang proaktif, yang terjadi justru sebaliknya. Pimpinan Tanfidziyah justru terkesan sebagai pengambil kebijakan dan dianggap representasi NU. Ini seolah-olah Syuriah berada di bawah pengaruh Tanfidziyah.
Dalam konflik-konflik itu, mekanisme di internal organisasi juga tidak lantas cair. Gus Solah mengatakan, ketika Tanfidziyah memasuki wilayah Syuriah, apakah pengurus NU sadar mekanisme organisasi? ”Kalau sadar organisasi, harusnya dipanggil, disemprit, (dikatakan) Anda melampaui wilayah itu. Ini harus dilakukan. Ini organisasi, bukan perorangan. Sekarang yang terjadi tidak seperti itu, Syuriah-nya ngomong di koran. Ini budaya organisasi yang tidak benar,” ujarnya.
Proporsional
Berdasarkan jejak-jejak itulah, sangat rasional apabila menjelang muktamar pekan ini suara-suara lantang meminta agar dikembalikannya peran lembaga masing-masing. Dalam rapat tim muktamar yang digelar di Pesantren Fatimiyyah Tambakberas, Jombang, pada 22 Februari, disepakati penguatan peran Syuriah sebagai lembaga tertinggi NU sesuai dengan AD/ART. Sebaliknya, ketika terkuak adanya wacana peran Syuriah akan dikebiri, perlawanan keras pun muncul.
Maka, melalui muktamar, ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, diharapkan bisa disatukan kembali ulama di Syuriah. Ketika memberi tausiyah pada penutupan Bahtsaul Masail Pramuktamar di Pesantren Ciwaringin, Cirebon, 31 Januari, kandidat rais aam Syuriah ini mengingatkan tentang pentingnya peran Syuriah, antara lain mengantisipasi ekstremisme dari luar, yang tidak bisa dihadapi lembaga Tanfidziyah.
Bagi Slamet Effendy Yusuf, dalam penataan organisasi itu perlu didorong dua lembaga tersebut melakukan fungsi dan peran secara proporsional. Syuriah agar dikembalikan lagi sebagai penentu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi, sedangkan Tanfidziyah sebagai pelaksana yang harus mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan Syuriah. Namun, kandidat ketua PBNU itu mengingatkan, penguatan Syuriah tidak lantas melemahkan Tanfidziyah. Penataan itu justru agar kedua lembaga itu harus saling memperkuat.
Penguatan Syuriah (dan Tanfidziyah) semestinya juga menjadi penguatan institusi NU secara keseluruhan. Apalagi, di NU, perangkat organisasi yang merealisasikan program NU cukup banyak, baik berupa lembaga (pelaksana kebijakan terkait bidang tertentu), lajnah (pelaksana program yang perlu penanganan khusus), maupun badan otonom (pelaksana kebijakan terkait masyarakat tertentu).
Selama ini, mekanisme yang terjadi, lembaga sebesar NU juga tak selalu segaris lurus. Bahkan, ditengarai, kebijakan hanya sampai pada tingkat pimpinan cabang di wilayah kota/kabupaten, tidak sampai ke akar rumput. Semestinya itu tak akan terulang lagi karena NU merupakan rumah puluhan juta orang umat.




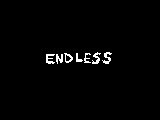




0 comments:
Post a Comment