Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

TRIBUN TIMUR/JUFRI
RABU, 24 MARET 2010 | 02:19 WITA
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 1984 menetapkan kembalinya organisasi NU ke Khittah NU 1926. Khittah itu mencakup banyak hal, antara lain dasar-dasar faham keagamaan NU; sikap kemasyarakatan NU; perilaku yang dibentuk oleh dasar dan sikap tersebut di atas, serta NU dan kehidupan berbangsa.
Butir ke-8 tentang Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Berbangsa cukup panjang dan menyeluruh, tetapi dalam wacana tentang NU, biasanya yang dimaksud dengan kembali ke Khittah NU adalah lepasnya organisasi NU dari ikatan dengan parpol manapun.
Hanya satu alinea yang menyinggung politik praktis. Alinea itu menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan apapun juga.
Sejak itu banyak tokoh NU yang bergabung dengan Golkar baik di pusat maupun daerah. Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) pernah menjadi anggota MPR mewakili FKP, tetapi tidak berapa lama lalu Gus Dur (GD) lantang mengkritik Pak Harto. Walaupun demikian jumlah tokoh NU yang aktif di dalam Golkar tetap banyak jumlahnya terutama di daerah.
Tergoda Parpol
Saat dibuka kesempatan untuk mendirikan parpol baru (1998), NU tergoda untuk mendirikan secara tidak langsung PKB yang diharapkan menjadi penyalur aspirasi politik warga NU. Di banyak tempat struktur NU aktif kampanye untuk PKB.
Dalam pemilu 1999 PKB memperoleh suara hampir 13 persen dari jumlah pemilih, padahal dalam pemilu 1955 Partai NU mendapat pemilih sekitar 18,4 persen. Berarti warga NU yang memilih partai-partai lain sedikit lebih banyak dibanding yang memilih PKB.
Mereka terutama banyak yang memilih PPP, Partai Golkar, selain PNU dan PKU. Dalam pemilu 2004 jumlah pemilih PKB sedikit menurun dan dalam pemilu 2009 makin menurun. Maka kita menghadapi fakta bahwa warga dalam pemilihan umum tersebar ke banyak partai.
Terpilihnya GD menjadi Presiden pada 1999 tampaknya makin menguatkan keyakinan banyak tokoh struktural NU bahwa sebaiknya NU terlibat dalam politik praktis. Pada 2004 Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi (HM) menjadi cawapres dari Megawati. Pemunculan HM sebagai cawapres terkesan direstui oleh Syuriyah PBNU yang mengizinkan HM hanya non-aktif saja, tidak harus mengundurkan diri.
Sejak itu banyak tokoh struktural NU di kabupaten/kota dan propinsi yang menjadi calon dalam pilkada. Bahkan dalam satu pilkada ada banyak tokoh NU yang menjadi calon. Maka tidak dapat dibantah bahwa pengurus NU sudah membawa organisasi NU ke wilayah politik praktis.
Lebih sulit lagi kondisi di Jatim saat beberapa tokoh NU maju sebagai calon dalam pilgub. Di banyak pemilihan, calon yang didukung struktural NU ternyata kalah. Kondisi itu dianggap merendahkan wibawa NU.
Melihat kondisi yang sangat tidak menggembirakan itu, maka banyak pihak di dalam kalangan NU yang mendesak supaya organisasi NU jangan terlibat lagi secara langsung dalam politik praktis atau politik kekuasaan, tetapi tetap bergelut dalam politik kebangsaan atau politik kemaslahatan umat. Tidak semua pihak berpikir seperti itu. Rais Syuriyah PWNU Jatim dan sejumlah kyai berpengaruh di Jatim masih ingin NU terlibat dalam praktis. Menurut mereka, kondisi saat ini amat berbeda dengan kondisi tahun 1984 saat Khittah NU 1926 ditetapkan oleh Muktamar NU.
Rupanya fakta lapangan kurang mereka perhatikan. Nyaris tidak mungkin untuk mendorong warga NU ke dalam satu partai saja. Warga dan aktivis NU tersebar ke banyak partai seperti PKB, PKNU, PPP, Golkar, Partai Demokrat, dan beberapa partai lainnya. Tidak heran bila semua bakal calon ketua umum PBNU menyatakan bahwa NU harus lepas dari politik praktis.
***
Saya menerima SMS yang berbunyi : "Aneh, bilangnya NU jangan dibawa ke politik praktis. Tapi kandidat Tanfidz-nya Gus Sholah dan Kang Said kok ketemu SBY "nyanyi" ke mana2. Kayak arenanya pemilihan Ketum Demokrat." Saya pikir pendapat pengirim SMS itu benar, dalam keadaan biasa. Tetapi saya menghadapi keadaan luar biasa, karena ada info yang sahih bahwa secara tidak terbuka beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa Presiden tidak menghendaki saya menjadi Ketua Umum PBNU.
Kabar burung itu beredar di banyak PCNU dan PWNU. Saya tidak memercayai kabar burung itu.
Pertemuan dengan Presiden terjadi karena saya mengajukan permohonan audiensi kepada presiden sejak akhir Januari untuk menyampaikan masalah membludaknya peziarah ke makam GD yang amat mengganggu kegiatan pendidikan dan pengajian di Pesantren Tebuireng dan mohon bantuan presiden. Beliau menyambut baik permohonan tersebut dan akan mengirim tim dari beberapa kementerian ke Tebuireng guna meninjau dan menyusun perencanaan bersama Pemkab Jombang, Pemprov Jatim dan Pesantren Tebuireng. Menurut Presiden SBY, karena Gus Dur adalah mantan presiden, maka pemerintah wajib membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan makam beliau.
Dalam kesempatan itu saya menanyakan kebenaran dari kabar burung di atas. Sama dengan dugaan saya, beliau membantahnya dan menyambut baik munculnya saya sebagai bakal calon ketua umum PBNU.
Beliau juga menyambut baik gagasan saya tentang perlunya kemitraan pemerintah dan NU dalam upaya memperjuangkan demokrasi ekonomi. Tentu pertemuan saya dengan presiden itu perlu disampaikan kepada publik untuk membantah kabar burung yang negatif bagi saya. Saya menduga pengirim SMS itu akan melakukan langkah yang sama dengan apa yang saya lakukan, kalau dia berada pada posisi saya.
***
Ada pengalaman lain berkaitan dengan masalah NU dan politik praktis. Awal Desember saya sowan Rais Aam PBNU Syuriyah KH Sahal Mahfud di Kajen, Pati. Dalam kesempatan itu saya sampaikan bahwa dalam Pilpres 2004 NU akan menghadapi masalah besar, ada potensi gesekan antartokoh NU dan pengikutnya. Rais Aam menanyakan apa maksud dari ucapan saya itu?
Saya sampaikan bahwa GD masih ingin menjadi capres melalui PKB dan HM juga ingin menjadi capres. Keadaan seperti itu adalah potensi perpecahan. Karena itu harus ada upaya untuk mengantisipasi potensi negatif itu. Yang bisa melakukannya adalah Rais Aam PBNU. Tidak ada lagi pihak lain yang bisa.
Rais Aam perlu memanggil GD dan HM, bisa terpisah, untuk menyampaikan bahwa dari kalangan NU harus ada hanya satu capres yang maju melalui PKB. Kalau GD bisa jadi capres, tanpa dikomando warga NU akan memilih GD. Tetapi kalau GD tidak bisa menjadi capres karena alasan kesehatan, maka PKB harus mencari capres dari kalangan NU dan PKB. PBNU bisa mengajukan beberapa calon yang bersama calon dari PKB akan dinilai oleh DPP PKB.
Menanggapi usulan itu, Rais Aam menyatakan tidak melakukan apa yang saya usulkan tadi. Karena menurutnya tindakan itu akan membawa organisasi NU ke dalam wilayah politik praktis. Dari satu segi, tindakan itu memang membuat NU masuk kedalam wilayah politik praktis, tetapi tujuannya adalah untuk mencegah dampak negatif terhadap jam'iyyah dan jamaah NU yaitu perpecahan.
Sejarah menunjukkan bahwa alih-alih memunculkan satu capres, dua tokoh PBNU (Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid) muncul sebagai cawapres dan keduanya kalah. Untung capres yang menang masih berasal dari komunitas NU yaitu Jusuf Kalla. Saya mengundurkan diri dari PBNU dan Hasyim Muzadi atas izin PBNU Syuriyah termasuk Rais Aam, hanya nonaktif.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa bagi Rais Aam langkah mengatasi potensi perpecahan dengan merekayasa adanya hanya satu capres dari kalangan NU, tidak bisa dilakukan karena dianggap memasuki wilayah politik praktis? Sedangkan langkah mengizinkan HM menjadi capres tanpa mengundurkan diri, yang nyata-nyata membawa dampak terseretnya NU kedalam wilayah politik praktis, justru dilakukan?
Dua kisah di atas tidak diangkat untuk mengungkit apa yang sudah lama berlalu dan menyalahkan siapapun, tetapi supaya bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk bisa menentukan mana yang layak dianggap sebagai langkah membawa NU kedalam politik praktis dan mana yang bukan.(*)




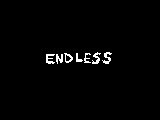




0 comments:
Post a Comment