 Saya berharap, NU sepeninggal Gus Dur justru akan lebih mapan, sanggup mengawal dinamika politik Indonesia dan menurun kadar tarik-ulur kepentingan sebagian elitnya.
Saya berharap, NU sepeninggal Gus Dur justru akan lebih mapan, sanggup mengawal dinamika politik Indonesia dan menurun kadar tarik-ulur kepentingan sebagian elitnya.
Yang saya maksud menjadi ‘lebih mapan’ sepeninggal KH Abdurrahman Wahid, tentu bukan karena meremehkan almarhum. Justru sebaliknya, ‘ketidakhadiran’ beliau secara fisik justru membangkitkan ingatan para kiai, bahwa kontroversi yang selama ini sengaja dimunculkan Gus Dur semata-mata merupakan strategi pendewasaan kaum nahdliyyin secara ‘alamiah’.
Tanpa kontroversi, baik kiai, pengurus dan warga NU bisa jadi terlena dengan kebesaran kwantitatifnya, sementara secara kwalitatif tak banyak kontribusinya terhadap ke-Indonesia-an seperti diangankan Gus Dur. Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan keyakinan.
Mungkin banyak yang tidak tahu, bahwa sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan satu-satunya organisasi Islam yang tidak terkontaminasi paham khilafah yang diperjuangkan ‘evangelis’ Wahabi. Hingga detik ini dan seterusnya, sikap NU terhadap bentuk negara Indonesia sudah final.
Haram hukumnya bagi warga NU, memberontak sebuah pemerintahan yang menjamin umat Islam menjalankan syariat agamanya, yakni rukun Islam yang lima. Selebihnya, termasuk di dalamnya hukum tata negara, hanya merupakan alat, siasat. Mungkin, itu yang dimaksud dengan pengertian fiqh siyasah.
Ketika menginisiasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, dugaan saya, itu semata-mata sebagai bentuk kanalisasi atas tingginya hasrat (ghiroh) politik warganya. Tanpa penyaluran yang benar, mustahil bisa diperoleh hasil yang besar, terutama menjadikan Indonesia Raya yang tenar, yang diperhitungkan perannya oleh negara-negara besar.
Yakin hasrat politik belum sebanding dengan kedewasaan bernegara, Gus Dur mengambil risiko besar. Membentuk struktur organisasi dengan dewan syuro sebagai posisi tertinggi yang diketuainya sendiri, sekilas tampak feodal, otoriter dan antidemokrasi. Saya yakin, Gus Dur sangat paham itu. Apalagi, di kemudian hari terbukti, PKB tak punya bargaining position yang berarti setelah perannya sebagai pemimpin tertinggi dilucuti secara sistematis lewat konspirasi tingkat tinggi.
Bahwa Gus Dur ingin selalu bisa mengontrol PKB, menurut saya, YA! Dalam angan idealnya, PKB ‘hanya’ merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan NU. Dan, kepentingan NU menurut Gus Dur, ya NU yang bukan sebatas jumlah warganya semata, namun lebih dari itu NU dalam konteks mengawal NKRI, yang terdiri bukan cuma segolongan saja. Bagi NU, terlalu banyak umat Kristen yang turut memanggul senjata memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga anak-cucu mereka berhak menuai perjuangan leluhurnya. Begitu pula kaum peranakan Cina, India, Arab, bahkan orang Belanda seperti Douwes Dekker alias Multatuli.
Islam bagi NU dan Gus Dur bukanlah yang mau menang-menangan dan merasa sebagai satu-satunya pemilik sah sebuah negara bernama Indonesia. Kata ‘Kristen’ tak bisa dipersepsikan sebagai ‘budaya’ penjajah. Sama halnya ketika warga peranakan Cina yang diberi tempat istimewa oleh Belanda demi memecah belah bangsa lantas dicap sebagai ‘antek’ mereka, sehingga harus dimusuhi.
Memang, pada tataran persepsi terhadap negara, bagi NU sudah selesai. Yang menjadi soal justru ketika sebagian elit NU melibatkan diri dalam kancah politik tanpa ketegasan sikap, maka yang dirugikan adalah umat. Politisi berlatar nahdliyyin yang tersebar di semua partai masih enggan tulus berkhidmad. Yang di PKB ingin menyeret NU ke PKB, begitu pula yang berada di Partai Golkar, PPP, dan partai-partai lainnya.
Mereka berharap NU membesarkan partai-partai mereka, bukan sebaliknya, bagaimana dari dalam partai-partai itu, mereka menyuarakan politik keumatan, sambil membesarkan NU dengan cara membiarkannya tetap netral, berdiri di atas semua golongan.
Satu pertanyaan saja yang perlu dijawab dengan sikap dan tindakan oleh para peserta muktamar: sanggupkah mereka memilih pimpinan NU yang bisa dimiliki pula oleh umat dari berbagai agama dan etnis seperti halnya ditunjukkan mereka terhadap Gus Dur?
Sejatinya, saya berharap pada KH A. Mustofa Bisri bersedia dicalonkan sebagai Ketua Tanfidziah NU, dengan KH A. Sahal Mahfudz sebagai pemimpin tertinggi syuriah. Terbukti, beliau belum pernah terkotori oleh noda-noda politik, dan memiliki moralitas yang sangat baik, seperti ditunjukkan keengganannya dicalonkan (apalagi mencalonkan diri) menjadi Ketua Tanfidziah atau Ketua Umum PBNU, setidaknya yang saya ikuti sejak Muktamar Lirboyo pada 1999.
Dengan dipimpin kiai tanpa noda politik, NU akan mampu menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, kekuasaan, juga semua golongan. Dalam keyakinan saya, mungkin kali ini Gus Mus akan kersa, ketika figur perekat antarakiai nyaris tinggal sedikit jumlahnya, dan masa depan Indonesia sudah di ambang bahaya, ketika gerakan-gerakan khilafah terus menjamur di seluruh penjuru Indonesia.
Sejatinya, keyakinan saya juga dilatari curiga. Bukan tak mungkin, kunjungan Gus Dur ke kediaman Gus Mus, beberapa hari menjelang wafatnya, telah menitipkan pesan atau wasiat kepada Kiai Mustofa Bisri. Sebuah pesan, agar beliau bersedia ‘turun gunung’ untuk memimpin NU, untuk mewujudkan cita-cita ke-Indonesia-an yang digagas para pendirinya, dan telah lama diperjuangkan Gus Dur, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir.
Semoga, ada kejutan dari Makassar, demi Indonesia Raya yang bhinneka.




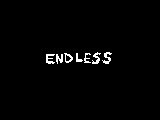




0 comments:
Post a Comment